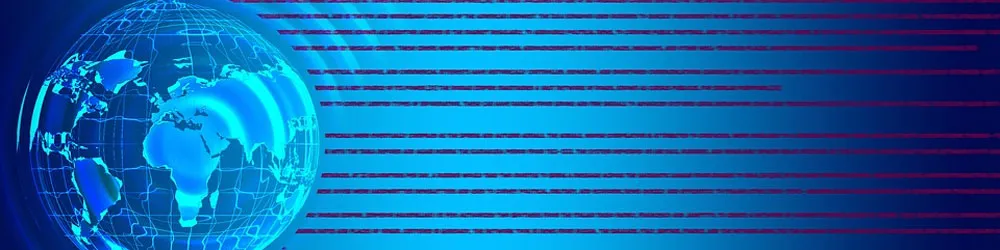Pemberian gelar haji bagi umat Islam setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci telah menjadi hal yang lumrah di Indonesia. Banyak dari mereka merasa bangga dengan gelar tersebut. Bagi laki-laki, mereka akan mendapat gelar haji, sementara perempuan akan disebut ‘hajjah’. Gelar ini bahkan disematkan di depan nama mereka. Siapa sangka, gelar-gelar ini sebenarnya tidak sesuai dengan aturan syariat Islam atau kerajaan Arab Saudi. Panggilan ini hanya ada di Indonesia.
Ternyata, kebiasaan ini bermula dari zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dua abad yang lalu, pergi haji tidak hanya dilihat sebagai urusan bisnis, ibadah, atau spiritual, tetapi juga memiliki dimensi politik. Para jamaah haji asal Indonesia seringkali dianggap “berulah” setelah pulang dari Makkah. Menurut kompeni, para jamaah ini sering belajar hal-hal baru selama di Tanah Suci. Ketika pulang ke kampung halaman, mereka pun menyebarkan ajaran-ajaran baru yang bisa memicu rakyat untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda.
Menurut Aqib Suminto dalam bukunya Politik Islam Hindia Belanda (1986), pikiran seperti ini pertama kali muncul pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1810-an. Daendels khawatir bahwa penduduk pribumi yang pulang dari haji dapat menghasut rakyat untuk memberontak. Oleh karena itu, ia meminta para jamaah haji untuk mengurus paspor haji sebagai tanda pengenal.
Pemikiran serupa juga muncul saat Indonesia dijajah oleh Inggris melalui Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles. Dalam catatannya berjudul History of Java (1817), Raffles bahkan secara terang-terangan menyerang orang-orang yang pergi haji. Ia menganggap bahwa orang Jawa yang pergi haji sok suci dan bisa menghasut rakyat untuk memberontak.